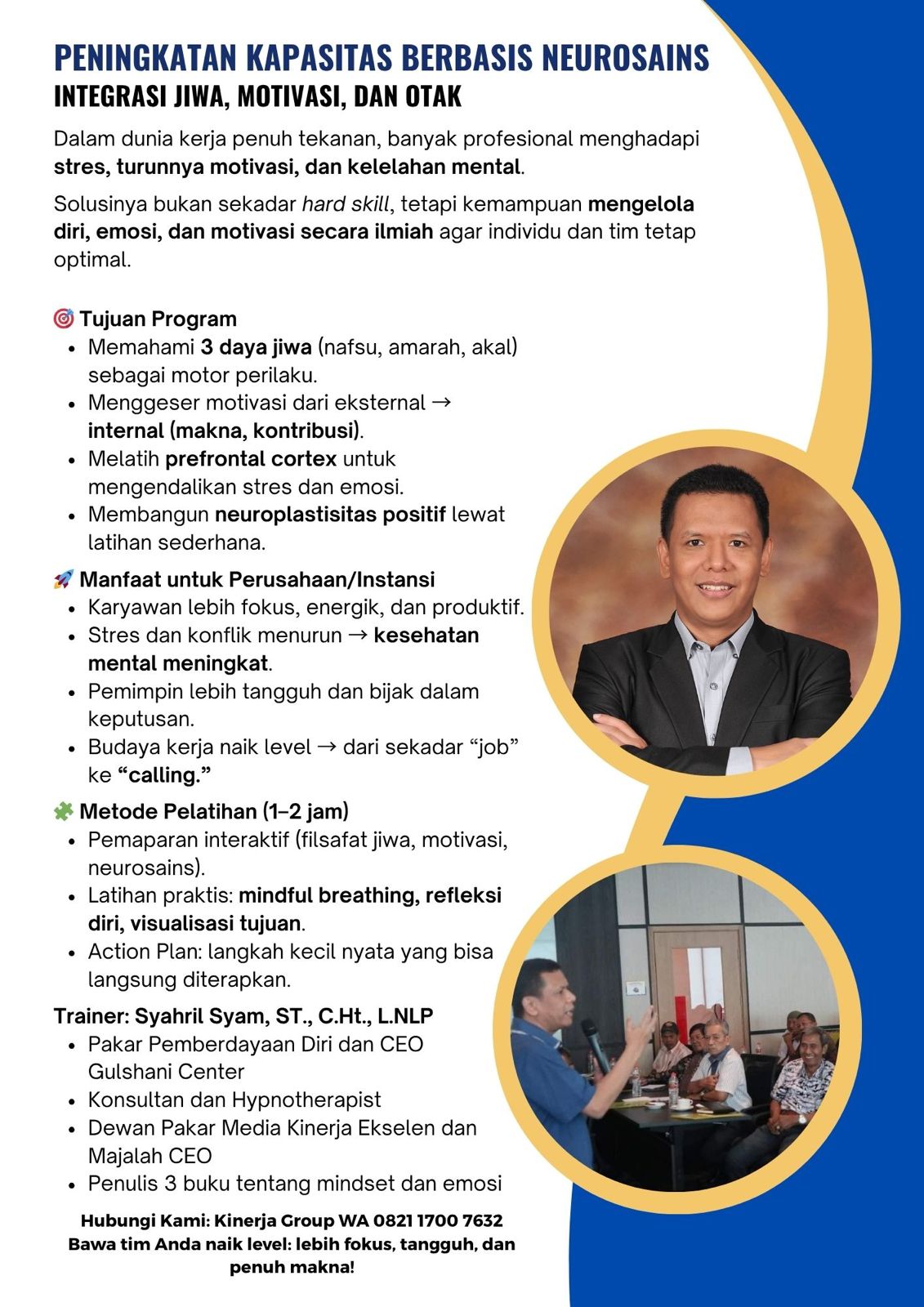Oleh Achmad Nur Hidayat – Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
Pertanyaan yang Menggelisahkan: Benarkah Uang Sitaan Korupsi Bisa Menyelesaikan Utang Whoosh?
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa utang proyek kereta cepat Whoosh bisa dibayar dengan uang hasil sitaan korupsi mengundang perhatian luas.
Di permukaan, gagasan ini tampak heroik: uang haram kembali untuk kepentingan publik.
Namun di balik pesan moral itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah sumber dana yang tidak pasti dapat menanggung beban proyek sebesar Whoosh secara berkelanjutan?
Proyek Whoosh bukan sekadar jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. Ia simbol ambisi negara besar — tetapi juga ujian bagi disiplin fiskal kita.
Ketika pembiayaan utang luar negeri dan biaya operasional mulai menekan, godaan mencari “jalan pintas” fiskal sering muncul.
Mengandalkan dana hasil sitaan korupsi termasuk salah satunya.
Masalahnya: Antara Harapan Politik dan Realitas Fiskal
Secara moral, ide ini menarik. Namun secara kelembagaan, ia sulit dijalankan.
Uang hasil sitaan korupsi masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggunaannya wajib melalui mekanisme APBN.
Besarannya pun fluktuatif. Tahun 2024, total setoran KPK dari uang rampasan hanya sekitar Rp637 miliar, sedangkan kebutuhan cicilan utang Whoosh mencapai lebih dari Rp1,2 triliun per tahun.
Artinya, bahkan seluruh hasil sitaan pun tidak cukup menutup kewajiban tahunan proyek.
Lebih jauh, penggunaan dana semacam ini tanpa aturan khusus berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan audit.
Negara memang boleh kreatif, tetapi kreativitas fiskal tidak boleh melanggar prinsip keberlanjutan.
Jika sumbernya tidak rutin, risiko fiskal meningkat dan kredibilitas keuangan negara bisa terganggu.
Menampung Air Hujan untuk Menutup Bocor
Mengandalkan uang sitaan korupsi ibarat menampung air hujan untuk menutup kebocoran atap rumah besar.
Air itu murni, datang tanpa biaya, tetapi tidak bisa diandalkan setiap hari.
Kebocoran harus diselesaikan dengan memperbaiki struktur atapnya — bukan menunggu hujan turun.
Demikian pula, masalah utang Whoosh tidak bisa disembuhkan dengan aliran dana yang sporadis.
Ia butuh perbaikan menyeluruh dalam desain pembiayaan proyek.
Mengapa Gagasan Ini Populer tapi Berisiko
Gagasan ini mendapat sambutan publik karena memadukan semangat anti-korupsi dan nasionalisme fiskal.
Namun secara ekonomi, pendekatan ini rawan menciptakan moral hazard.
Bila proyek gagal menghasilkan pendapatan, lalu diselamatkan dari pos sitaan, pesan yang tersampaikan adalah bahwa proyek besar tak perlu diaudit secara keras — selalu ada “dana ajaib” yang menolong.
Ini bisa menurunkan disiplin fiskal dan menciptakan preseden buruk bagi proyek strategis lainnya.
Selain itu, proyek Whoosh merupakan hasil kerja sama dengan konsorsium Tiongkok melalui China Development Bank.
Kontrak pinjaman bersifat multi-tahun 50 tahun dan ketat. Ketidakkonsistenan dalam pembayaran akan berdampak pada reputasi Indonesia di mata investor global.
Solusi yang Lebih Sehat: Kreativitas Finansial Lewat Danantara
Penyelesaian terbaik utang Whoosh seharusnya tidak melalui APBN, pajak, atau PNBP sitaan korupsi, tetapi melalui financial creativity.
Di sinilah peran Danantara, lembaga pengelola investasi negara (sovereign wealth fund), menjadi kunci.
Danantara memiliki fleksibilitas untuk melakukan refinancing atau debt restructuring tanpa menambah beban fiskal langsung. Bahkan Aset Danantara termasuk yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan aset sebesar itu seharusnya persoalan KCJB adalah hal yang mudah.
Skemanya bisa berupa debt-to-equity swap bersama konsorsium Tiongkok, perpanjangan tenor, atau penerbitan obligasi infrastruktur berbasis aset proyek.
Selain itu, monetisasi kawasan sekitar stasiun — transit-oriented development (TOD), hak guna lahan, dan bisnis komersial — dapat menciptakan arus pendapatan mandiri.
Inilah bentuk kreativitas fiskal yang sejati: mengubah proyek yang semula membebani menjadi instrumen produktif, bukan sekadar menambal dengan uang sitaan yang datang tak menentu.
Belajar dari Negara Lain: Infrastruktur yang Menciptakan Nilai, Bukan Disubsidi
Brasil dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa proyek transportasi besar bisa mandiri jika dikaitkan dengan penciptaan nilai ekonomi baru.
Land value capture dan kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek menghasilkan pendapatan di luar tiket.
Indonesia bisa meniru pendekatan ini: menjadikan Whoosh sebagai ekosistem ekonomi, bukan hanya sarana transportasi berbiaya tinggi.
Risiko Jika Diteruskan: Negara Kehilangan Disiplin Fiskal
Menjadikan uang sitaan korupsi sebagai sumber pembiayaan proyek dapat menurunkan disiplin kelembagaan.
BUMN dan kementerian bisa terbiasa bergantung pada sumber “tak terduga” ketika menghadapi masalah finansial. Ini bukan hanya persoalan fiskal, tapi juga etika kebijakan publik. Negara seolah memberi pesan bahwa proyek gagal bisa ditebus dengan uang dari dosa masa lalu.
Moralitas Harus Sejalan dengan Rasionalitas Fiskal
Presiden Prabowo benar ketika menyatakan bahwa uang haram harus dikembalikan kepada rakyat.
Tetapi pengelolaan keuangan publik tidak boleh bersandar pada moralitas semata. Uang sitaan korupsi bisa digunakan untuk simbol keadilan — membangun sekolah, fasilitas publik, atau riset antikorupsi — tetapi tidak untuk menutup kewajiban komersial proyek besar.
Utang Whoosh perlu diselesaikan dengan strategi fiskal yang rasional: restrukturisasi dengan konsorsium Tiongkok, dukungan kreatif dari Danantara, dan monetisasi aset produktif.
Hanya dengan cara itu, Whoosh benar-benar menjadi simbol kemajuan — bukan kecepatan yang menambah beban.
End